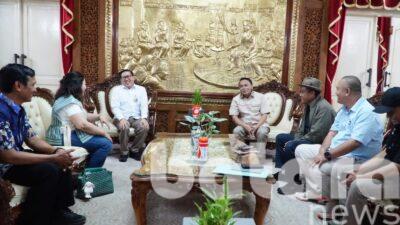Nagari Salareh Aia, Palembayan — Di antara kepulan asap wajan besar, deru generator kecil, dan aroma sayur panas yang mengepul dari Dapur Umum Lapangan (Dumlap) Kementerian Sosial RI, seorang pria berdiri tegap.
Seragam Tagana (Taruna Siaga Bencana) berwarna hijau tua melekat di tubuhnya, basah sebagian karena keringat. Namanya Wirman Saputra, 16 tahun bergabung sebagai Taruna Siaga Bencana Kementerian Sosial RI.
Di dapur darurat itulah, di tengah aktivitas relawan yang menyiapkan ribuan porsi makanan Wirman menceritakan ulang kisah yang sudah berhari-hari tersimpan di dadanya: kisah ketika galodo menerjang Kampung Sikumbang, Jorong Subarang Aia, Palembayan, Kabupaten Agam.
Ia tidak duduk. Ia bercerita sambil berdiri. Sesekali kedua tangannya menopang pinggang, kadang menunjuk ke arah bukit seolah peristiwa itu masih berada tepat di depan matanya.
Tatapannya menembus jauh melewati tenda, melampaui halaman posko, menuju kampungnya yang berada hanya beberapa kilometer dari dapur umum ini. Kampung yang kini rusak parah, penuh lumpur, dan meninggalkan jejak kelam peristiwa itu.
Suara Wirman mantap, yakin, dan jernih. Tidak ada getar ketakutan ketika ia mengingat peristiwa besar itu. Yang terlihat justru ketegasan seorang penyelamat yang masih berada dalam mode siaga, seolah tubuhnya belum benar-benar keluar dari situasi darurat.
Dan dari caranya memandang, jelas bahwa ia tidak sekadar mengenang. Ia sedang memutar ulang setiap detik mencekam itu.
“Semua terjadi begitu cepat, bu… suara itu macam pesawat mau landing.”
Hari itu Kamis (27/11) sore. Wirman baru pulang setelah dua hari bertugas di kecamatan lain untuk menangani banjir. Ia berniat hanya mengambil pakaian, lalu kembali turun membantu.
Namun istrinya, dengan wajah cemas dan suara tegas, menahannya sebentar.
“Makan dulu. Udah dua hari tak pulang.”
Wirman mengulang kalimat itu sambil tersenyum kecil. Senyum yang mengendap dari rasa syukur karena keputusan sederhana itu menyelamatkan nyawanya.
Namun ketika ia baru saja meraih kunci motor untuk kembali bertugas, bumi seperti mengirim peringatan.
“Tiba-tiba saya dengar suara bising… kuat sekali. Macam pesawat landing dari bukit.”
Ia membuat gerakan tangan menukik tajam ke bawah, menirukan suara besar yang datang dari arah hulu.
Tanah bergetar.
Piring di rak berderak.
Suara orang berteriak dari luar.
Kampung Sikumbang yang jaraknya hanya 75 meter dari sungai, menjadi salah satu titik yang paling cepat merasakan getaran itu.
Istrinya panik, hendak lari ke luar rumah.
Namun Wirman yang masih mengingat setiap detik pelatihan Tagana seumur hidupnya menahan bahunya dengan penuh keyakinan.
“Jangan keluar. Kita bertahan dulu. Yang besar datang sekali. Setelah itu baru bergerak.”
Dari matanya saat ia berkata begitu, terlihat jelas bahwa bukan keberuntungan yang membuatnya selamat, tetapi ketepatan bacaannya terhadap situasi.
Ia kemudian menggambarkan momen itu dengan suara rendah namun tajam.
“Air besar, bu… tingginya lebih kurang 40 meter di belakang rumah. Cepat sekali.”
Rumah bergoyang. Hawa dingin bercampur lumpur masuk dari sela-sela kayu.
Namun setelah suara terbesar lewat, Wirman tidak menunggu.
Ia keluar rumah melawan naluri dasar manusia untuk bertahan di tempat aman.
Dari arah kolam, terdengar seseorang menggerak-gerakkan tangan, tenggelam setengah badan dalam lumpur dan air keruh.
Tanpa memikirkan risiko susulan, Wirman melompat ke arah korban.
“Saya selamatkan. Tarik ke rumah.”
Ia memegang pergelangan tangan korban seolah masih merasakannya. Air hujan yang membasahi seragamnya saat ini seperti menyatu dengan cerita yang ia ulang.
Di dalam rumah, istrinya memandikan korban itu, mengusap wajahnya, menyingkirkan lumpur yang menutup hidung dan mulut.
“Hidup lagi orangnya.”
Nada puas terdengar halus dalam suaranya tak berlebihan, hanya ketulusan.
Tidak lama, suara jeritan lain datang.
Seorang nenek, sekitar 68 tahun, berdiri gemetaran, tubuhnya tanpa pakaian karena tersapu arus, wajahnya hampir tak terlihat tertutup lumpur pekat.
“Kasihan kali, bu. Saya langsung gendong.”
Dengan gerakan spontan yang ia peragakan di dapur umum, ia menggambarkan posisi tubuh sang nenek yang ringkih.
Nenek itu diselamatkan. Diperbaiki martabatnya. Dibersihkan. Dihangatkan.
Evakuasi Ketiga, seorang anak laki-laki 11 tahun yang nyaris tenggelam.
“Anak kecil itu nadinya sudah lemah. Nafasnya susah.”
Di bawah cabang kayu besar yang tersangkut, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun hampir tenggelam.
Wirman mengangkat tangan kanannya, menggambarkan bagaimana ia meraih tubuh mungil itu dengan cepat, menahan kepalanya agar tidak kembali masuk lumpur.
“Saya gendong langsung. Bawa ke rumah.”
Anak itu hidup. Matanya yang tadi nyaris hilang di balik lumpur kini kembali tampak, berkat gerakan cepat Wirman.
Suara berikutnya datang dari pematang sawah. Seorang korban berteriak, namun terlalu dalam terjebak lumpur. Wirman mencoba mengangkatnya, namun tak bisa.
Ia keluar masuk rumah, mengambil terpal lebar, merentangkannya di atas lumpur, menidurkan korban di atas terpal, dan menariknya menyusuri lumpur yang licin dan penuh batang kayu.
“Tarik pelan-pelan, zig-zag. Kayu banyak sekali.”
Ia menggambar jalurnya dengan menggambar di udara. Jarinya bergerak lincah, seolah lumpur itu masih di bawah kakinya.
Dalam waktu kurang dari satu jam,
empat nyawa semuanya dalam kondisi kritis berhasil ia selamatkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang kehilangan nyawa hari itu.
Kampung Sikumbang kini porak-poranda. Jalan terputus. Akses ke dalam desa hanya bisa lewat jembatan darurat dan itu pun jika air tidak sedang naik.
“Bantuan ada, bu. Tapi banyak terhenti di luar. Ke dalam yang sulit. Kami maklum, akses semua putus.”
Ia mengatakannya tanpa menyalahkan siapa pun. Suaranya tetap datar dan objektif gaya bicara seseorang yang terbiasa bekerja di medan sulit.
Warga kini banyak yang bergantung pada Dapur Umum Lapangan tempat Wirman berdiri menggenggam cerita.
“Selama kami bisa nyeberang, kami keluar cari makan. Pagi, siang, malam. Untuk warga.”
Ketika diminta memberi pesan untuk sesama Tagana, matanya kembali meredup namun tetap tenang.
“Ikhlas nomor satu. Jangan berharap apa-apa. Kepuasan menolong itu yang paling besar.”
Ia mengucapkannya sambil menghela napas pelan, mengusap seragam hijau tua yang masih menempel lumpur halus di bagian lengan.
Wirman bukan hanya penyintas. Bukan hanya relawan. Ia adalah denyut keberanian Kampung Sikumbang. Di dapur umum yang sibuk ini di mana suara sendok beradu dengan panci, aroma nasi panas bercampur dengan bau tanah basah, dan tenda putih bergoyang tertiup angin, Wirman berdiri tegap.
Tidak ada air mata.
Tidak ada suara yang pecah.
Tidak ada getaran ketakutan.
Yang ada adalah sorot mata seorang lelaki yang telah melihat kematian datang dari arah bukit lalu memilih berlari ke arahnya untuk menarik orang lain keluar.
Sorot mata yang memandang jauh, seolah masih memotret adegan demi adegan yang datang terlalu cepat hari itu:
Gelombang air besar.
Jeritan warga.
Tubuh-tubuh berlumur lumpur.
Empat nyawa yang kembali bernapas.
Ketika galodo mengoyak kampungnya, Wirman tidak hanya selamat.
Ia membuat orang lain selamat bersamanya.
Dan di tengah hiruk-pikuk Dapur Umum Lapangan Kemensos RI, keberaniannya berdiri seperti tiang tenda yang tak goyah di tengah angin diam namun memikul beban yang sangat besar.
Kampung Sikumbang boleh porak-poranda.
Namun keberanian warganya yang bernama Wirman Saputra tetap tegak, dan kisahnya kini menjadi bagian dari cara kampung itu bangkit kembali.